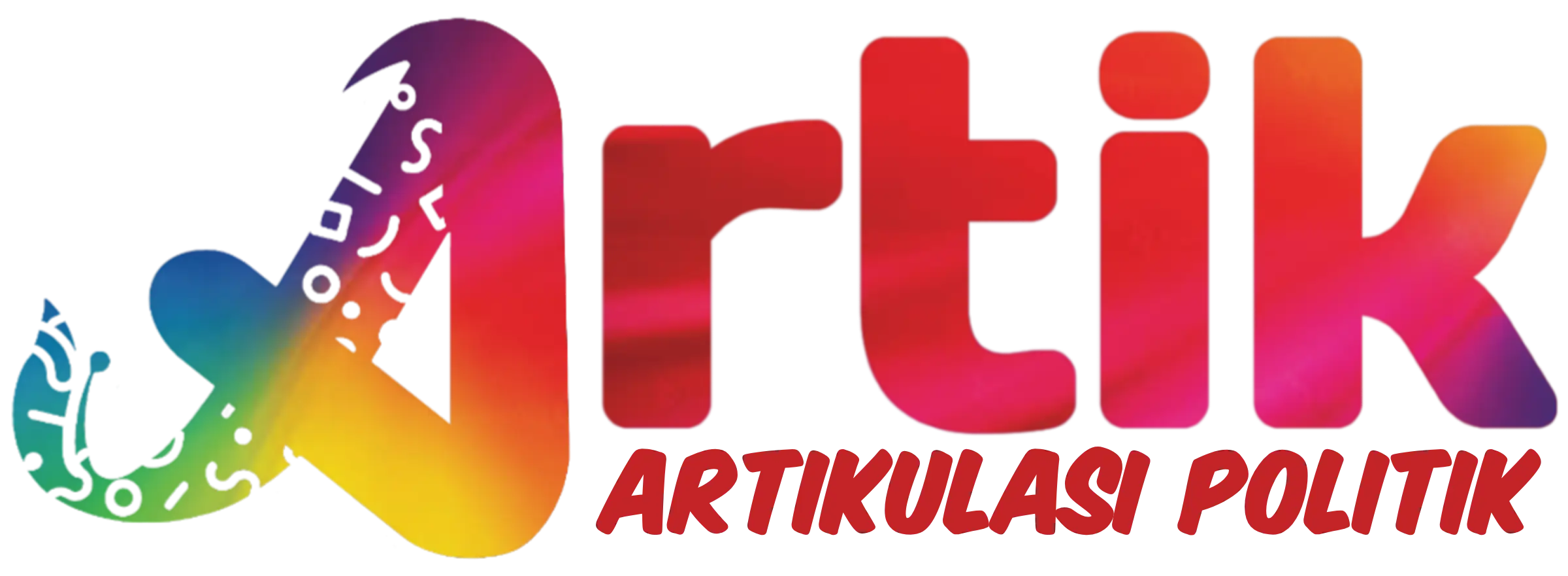BAWEAN - Di tengah derasnya arus modernisasi, masyarakat Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, masih memegang erat nilai-nilai gotong royong melalui tradisi Atolong. Tradisi yang telah diwariskan turun-temurun ini menjadi bentuk nyata kepedulian sosial masyarakat dalam dua momen penting kehidupan: pernikahan dan kematian.
Atolong bukan sekadar kegiatan saling membantu, melainkan cerminan jati diri, solidaritas, dan kebersamaan masyarakat Bawean. Melalui tradisi ini, nilai-nilai sosial, spiritual, dan budaya menyatu dalam praktik kehidupan sehari-hari.
Dalam setiap hajatan, semangat kebersamaan masyarakat Bawean begitu terasa. Seluruh lapisan warga, mulai dari orang tua hingga remaja bahu-membahu menyiapkan berbagai keperluan acara. Para pria bersama remaja laki-laki bergotong royong mendirikan tarop (tenda hajatan), mengambil bambu, serta membantu mengangkut perlengkapan dari rumah pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan, prosesi yang dikenal dengan istilah mamasang.
Peran remaja juga tak kalah penting dalam setiap pelaksanaan tradisi Atolong. Mereka turut membantu membuat pelangki, yaitu tandu yang digunakan untuk menggotong pengantin laki-laki atau perempuan. Pelangki biasanya dibuat dari bambu, kemudian dihias dengan kain berwarna cerah, janur, dan ornamen tradisional agar tampak indah saat digunakan dalam arak-arakan pernikahan.
Selain itu, para remaja juga bertugas membuat umbul-umbul yang terbuat dari batang bambu dengan jeruk atau pepaya di bagian atasnya. Pada ujung umbul-umbul tersebut biasanya disematkan uang sebagai simbol kemeriahan dan rasa syukur. Umbul-umbul ini kemudian diarak bersama rombongan pengantin dari rumah mempelai laki-laki menuju rumah mempelai perempuan dalam prosesi ngereng-ngereng, menciptakan suasana yang meriah dan penuh makna kebersamaan.
Kaum perempuan, baik dewasa maupun remaja, turut berperan melalui bantuan tenaga dan materi. Mereka memasak bersama, menyiapkan hidangan untuk tamu, serta memberikan bantuan berupa bherkat (paket makanan) atau uang kepada keluarga penyelenggara. Semua bentuk partisipasi ini menjadi cerminan nyata dari nilai Atolong atau tolong-menolong yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat Bawean.
Dalam pelaksanaannya, Atolong mencakup empat bentuk bantuan utama, yakni tenaga, barang, uang, dan pengetahuan. Masyarakat terlibat aktif dalam setiap kegiatan, mulai dari mendirikan tenda, menyiapkan perlengkapan upacara, hingga memberikan sumbangan untuk meringankan beban keluarga penyelenggara acara.
“Siapa yang ingin dibantu, maka harus siap membantu orang lain,” ujar salah satu warga Desa Gunung Teguh, menggambarkan prinsip timbal balik sosial yang masih dipegang teguh hingga kini.
Tahapan awal tradisi ini disebut remo-remo atau kompol-kompol, yakni pertemuan keluarga dan warga untuk menentukan hari baik pernikahan serta mencatat bentuk bantuan yang diberikan. Warga biasanya membawa bahan pokok seperti beras, tepung, atau gula sebagai wujud dukungan.
Puncak prosesi pernikahan ditandai dengan ngereng-ngereng, arak-arakan pengantin yang diusung menggunakan pelangki—tandu kayu berhias kain warna-warni, diiringi tabuhan tetebbhuen serta rojali (umbul-umbul dengan uang) sebagai simbol kebahagiaan dan keberkahan.
Di Desa Gunung Teguh, masyarakat masih mempertahankan ritual ghusok (lulur kunyit) dan aokep (masa pengasingan calon pengantin perempuan sebelum menikah). Ritual ini melambangkan penyucian diri dan kesiapan lahir batin untuk membangun rumah tangga.
Sementara itu, upacara manyengse ojhen atau sarang dilakukan untuk menolak hujan saat acara berlangsung. Warga menancapkan sapu lidi dengan bawang dan cabai, membakar batu bata, atau menyalakan besi panas sebagai simbol permohonan kepada alam agar cuaca tetap cerah.
Dalam tradisi Atolong, setiap benda dan prosesi memiliki makna simbolik yang mendalam. Bherres koneng (beras kuning) melambangkan doa keselamatan dan keberkahan.Tetebbhuen yang terdiri dari tebu, pinang, dan sirih merepresentasikan keberanian dan kekuatan. Sedangkan ongkek, susunan hiasan yang diarak pada pernikahan anak laki-laki terakhir, menjadi tanda tuntasnya tanggung jawab keluarga dan doa agar rumah tangga baru penuh keberkahan.
Simbol lain seperti pelangki menggambarkan kemuliaan mempelai, sementara bherkat mencerminkan semangat berbagi rezeki yang mengikat hubungan sosial antarwarga. Makna-makna simbolik ini sekaligus memperlihatkan perpaduan nilai budaya lokal Bawean dengan ajaran Islam yang menekankan solidaritas dan kebersamaan.
Atolong dalam Prosesi Kematian
Sejak malam pertama hingga hari ke-40 setelah kematian, warga bersama para remaja bergiliran datang ke rumah duka untuk membaca doa dan mengaji bersama. Tradisi yang dikenal dengan sebutan mellek-mellek ini dilakukan sebagai bentuk empati dan dukungan moral bagi keluarga yang ditinggalkan. Sebagian warga bahkan memilih untuk bermalam di rumah duka agar keluarga yang berduka tidak merasa sendiri selama masa pengajian dan doa berlangsung.
Tradisi sango-sango pun masih lestari, yakni pemberian hidangan khusus kepada saudara laki-laki tertua almarhum sebagai bentuk penghormatan terakhir.
Di beberapa desa, keluarga juga membelah kelapa di makam jenazah yang baru dikubur sebagai simbol berakhirnya garis keturunan tertentu, atau menabur kacang hijau di atas tanah pemakaman sebagai bentuk doa untuk kelanjutan amal kebaikan.
Hingga kini, Atolong masih menjadi penopang kehidupan sosial masyarakat Bawean. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memperkuat kohesi sosial, mempererat hubungan antargenerasi, dan menjadi pedoman hidup bagi warga pulau.
Pelestarian tradisi ini tidak hanya penting sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sarana pendidikan karakter dan pembentukan empati sosial di tengah perubahan zaman. Jika dijaga dengan baik, Atolong akan terus menjadi cermin kearifan lokal masyarakat Bawean yang tak lekang oleh waktu.
Makna Sosial dan Pesan Kemanusiaan
Penelitian ini dilakukan oleh tim mahasiswa Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya melalui program PKM-RSH, yang beranggotakan Siti Amriyah, Luna Rindi Rahmawati, dan Caroline Maria Desi Kaanubun, dengan dosen pendamping Haerussaleh, S.Pd., M.Pd. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa Atolong bukan sekadar praktik sosial, melainkan juga bentuk komunikasi budaya yang menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat Bawean.
“Tradisi ini mengajarkan nilai empati, tanggung jawab sosial, dan rasa persaudaraan yang kuat. Semua prosesi dan simbolnya menjadi cara masyarakat berinteraksi dan mempertahankan harmoni,” ungkap Amriyah.
Dengan pendekatan sosiosemiotika, ia menemukan bahwa Atolong memadukan makna sosial dan simbolik: tenaga menjadi tanda solidaritas, uang dan barang sebagai simbol tolong-menolong, dan setiap ritual menjadi refleksi spiritual yang memperkuat identitas Bawean.
Penulis: Siti Amriyah – Mahasiswi Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Penelitian dilakukan di Pulau Bawean, Gresik, dengan fokus pada makna sosial dan simbolik tradisi Atolong melalui pendekatan sosiosemiotika.
Editor : Fudai