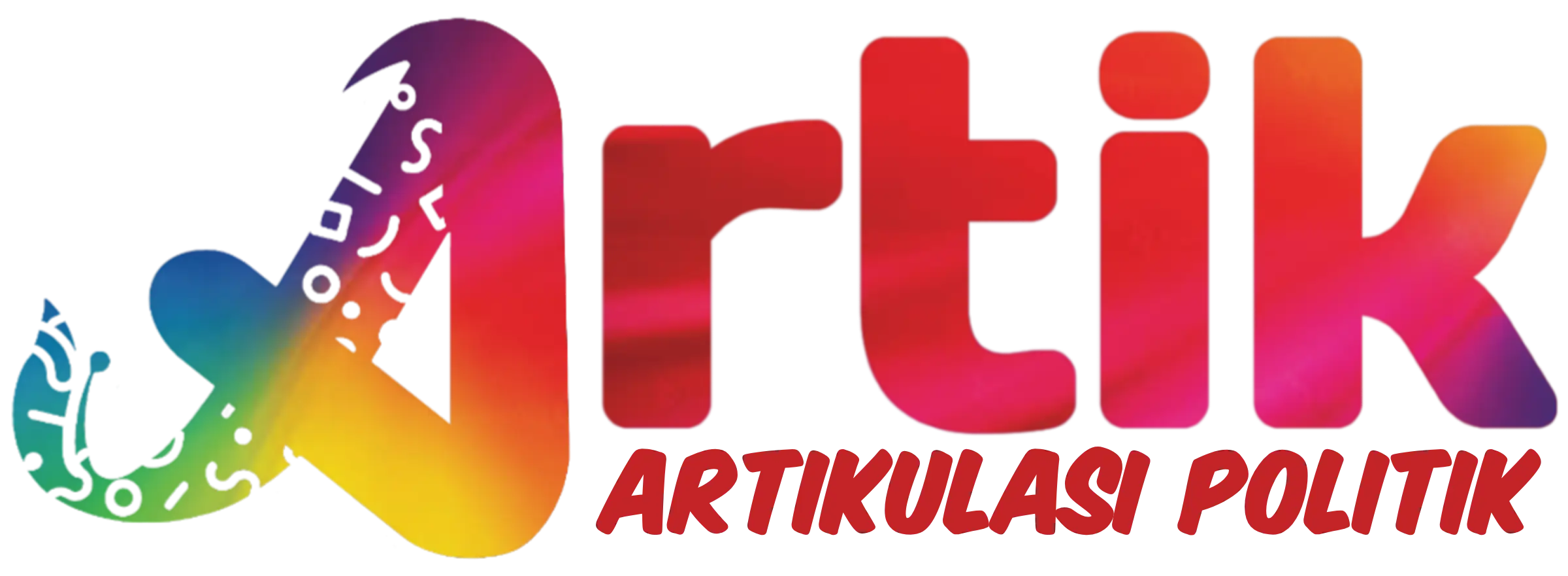Politik Ekonomi RI: Fiskal Neoliberal, Keadilan Sosial Tumbal
Oleh : Abdul Rasyid
Politik ekonomi Indonesia tidak pernah lepas dari perdebatan ideologi, sejak awal kemerdekaan, arah kebijakan ekonomi selalu dipengaruhi oleh konfigurasi politik, kepentingan elit, dan dinamika global.
Kebijakan fiskal Indonesia menunjukkan dinamika ideologis yang sangat erat kaitannya dengan perubahan politik dan ekonomi. Menteri Keuangan sebagai aktor teknokrat memegang peranan strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus merespons kebutuhan sosial politik rakyat.
Periode kepemimpinan Ali Wardhana pada era Orde Baru, Bambang Sudibyo pada awal Reformasi, dan Sri Mulyani Indrawati pada era Reformasi kontemporer, mencerminkan pergeseran orientasi fiskal: dari kapitalisme negara-pembangunanisme, ke populisme kerakyatan, hingga neoliberalisme teknokratis saat ini, merupakan perjalanan Politik Ekonomi Indonesia mengalami transformasi ideologi yang dinamis sekaligus penuh kontradiksi.
Kapitalisme Negara Era Orde Baru
Pada masa Orde Baru, pembangunan ekonomi dijalankan dengan model kapitalisme negara. Negara menjadi aktor utama dalam mengendalikan sumber daya strategis, namun pada saat yang sama membuka pintu bagi konglomerasi swasta yang dekat dengan kekuasaan.
Ali Wardhana - Menteri Keuangan 1973 - 1983 berperan sebagai arsitek fiskal Orde Baru yang menopang legitimasi politik otoritarian Soeharto. Sumber utama penerimaan negara adalah minyak bumi dan bantuan luar negeri dari IGGI/CGI. Kebijakan fiskalnya menekankan disiplin anggaran dan stabilitas makro, tetapi tetap mempertahankan subsidi besar pada energi dan pangan untuk menjaga stabilitas harga.
Ideologinya dapat dikategorikan sebagai kapitalisme negara-pembangunanisme : Negara menjadi aktor dominan dalam mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur, Revolusi Hijau, dan industrialisasi awal.
Dampak sistem kapitalisme negara, menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi 7 - 8% per tahun (era 1980 - 1990-an), tetapi juga menumbuhkan praktik oligarki dan ketergantungan pada hutang luar negeri. Stabilitas politik dijaga ketat melalui kontrol represif, sementara distribusi kekayaan terjadi ketimpangan sosial makin tajam.
Populisme Fiskal Era Reformasi
Reformasi 1998 membawa semangat demokratisasi yang membuka ruang bagi “populisme fiskal”. Pemerintah mulai menerapkan kebijakan subsidi luas (BBM, listrik, pupuk), program bantuan sosial, dan redistribusi untuk merespons tuntutan rakyat yang lama ditekan.
Bambang Sudibyo, Menteri Keuangan 2004 - 2005, menghadapi tantangan APBN yang rapuh akibat krisis 1997/1998, ia tidak langsung melakukan disiplin fiskal, tetapi memilih mempertahankan subsidi energi untuk menjaga harga murah dan mencegah gejolak sosial-politik.
Langkah ini menunjukkan kecenderungan populis-kerakyatan, di mana legitimasi pemerintah baru lebih diutamakan ketimbang konsistensi anggaran.
Meski membantu rakyat dalam jangka pendek, kebijakan ini dinilai tidak efisien : subsidi lebih banyak dinikmati kelas menengah-atas (pemilik mobil pribadi), sementara APBN semakin terbebani.
Orientasi ideologi Bambang dapat diposisikan sebagai ekonomi populis : pro rakyat dalam retorika harga murah, tetapi rapuh dalam fondasi fiskal.
Populisme fiskal ini memberi legitimasi politik, namun seringkali tidak berkelanjutan karena bertabrakan dengan keterbatasan fiskal negara. Ketika harga minyak naik atau krisis global menghantam, kebijakan populis ini menimbulkan beban anggaran besar dan menekan stabilitas ekonomi.
Neoliberalisme Teknokratis
Ketika Sri Mulyani, Menteri Keuangan 2005 - 2010 ; menggantikan Bambang Sudibyo, dan menjabat lagi pada 2016 sampai dengan awal September 2025, melakukan perubahan signifikan.
Subsidi energi dipangkas secara bertahap, dan dana dialihkan ke program sosial seperti BLT, PKH, pendidikan, dan kesehatan.
Sri Mulyani juga memperkuat penerimaan pajak, membatasi defisit ≤3% PDB, serta mengandalkan instrumen pasar (obligasi negara, rating utang) untuk memperkuat kredibilitas fiskal.
Ideologinya mencerminkan neoliberalisme teknokratis : disiplin fiskal, keterbukaan terhadap pasar global, transparansi, serta integrasi dengan standar internasional (World Bank, IMF). Perlindungan sosial diberikan, tetapi bersifat kompensatoris, bukan struktural. Dengan kata lain, rakyat tidak lagi “dilindungi lewat harga murah”, melainkan diberi jaring pengaman sosial ketika harga pasar naik.
Di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan seperti Sri Mulyani, arah politik ekonomi Indonesia semakin kental dengan nuansa neoliberalisme teknokratis. Karakter utamanya, :
1. Disiplin fiskal ketat melalui defisit anggaran rendah.
2. Privatisasi dan deregulasi sektor strategis dengan alasan efisiensi.
3. Peran teknokrat yang lebih dominan ketimbang politisi dalam perumusan kebijakan.
4. Integrasi ke pasar global melalui investasi asing, liberalisasi perdagangan, dan reformasi birokrasi.
Neoliberalisme teknokratis ini menjaga stabilitas makroekonomi dan meningkatkan kepercayaan investor internasional, tetapi sering dikritik karena kurang berpihak pada rakyat kecil. Subsidi dipangkas, sementara infrastruktur dan stabilitas fiskal lebih diutamakan.
Ketimpangan Sosial
1. Kapitalisme Negara Orde Baru menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi (rata-rata >7% pada 1980-an), tetapi distribusi kekayaan sangat timpang. Konglomerasi yang dekat dengan kekuasaan menikmati rente ekonomi, sementara rakyat kecil tetap bergantung pada subsidi harga pokok.
2. Populisme Fiskal memberi ruang redistribusi lebih luas, seperti subsidi BBM, BLT, dan program bantuan sosial. Namun sifatnya jangka pendek sehingga gagal menciptakan keadilan struktural.
3. Neoliberalisme Teknokratis menekan subsidi dengan alasan disiplin fiskal. Hal ini menekan defisit, tetapi juga membebani kelas menengah ke bawah, memperbesar kesenjangan sosial-ekonomi.
Ketiga model belum berhasil secara berkelanjutan menurunkan ketimpangan, meski dengan pendekatan berbeda.
Kedaulatan Ekonomi
1. Kapitalisme Negara mempertahankan kedaulatan melalui BUMN dan kontrol negara atas SDA. Namun, ketergantungan pada utang luar negeri membuat Indonesia rapuh saat krisis 1997/1998.
2. Populisme Fiskal memperkuat legitimasi domestik, tetapi tetap mengandalkan dana pinjaman luar negeri dan bantuan lembaga internasional (IMF, Bank Dunia).
3. Neoliberalisme Teknokratis meningkatkan integrasi pasar global, menarik investasi asing, dan menjaga rating utang. Namun, ini memperlemah otonomi negara dalam menentukan arah kebijakan, karena sangat dipengaruhi ekspektasi pasar internasional.
Semua fase memperlihatkan ketergantungan struktural pada kapital global, dengan hanya beda variasi cara dalam pengelolaannya.
Stabilitas Politik dan Legitimasi
1. Kapitalisme Negara Orde Baru menjaga stabilitas melalui kontrol represif, namun kehilangan legitimasi saat krisis melanda.
2. Populisme Fiskal mengandalkan redistribusi untuk meraih legitimasi, tetapi rawan dianggap sebagai politik uang terselubung.
3. Neoliberalisme Teknokratis lebih stabil di tingkat makroekonomi, namun rawan delegitimasi politik karena rakyat merasakan beban ekonomi tanpa perlindungan memadai.
Tidak ada model yang mampu menciptakan stabilitas politik yang sepenuhnya kokoh; justru setiap model melahirkan potensi krisis legitimasi dalam konteks berbeda.
Hibridasi Idoelogi dan Ambivalensi
Indonesia saat ini berada pada persilangan antara populisme elektoral (misalnya bansos menjelang pemilu), kapitalisme negara (proyek infrastruktur melalui BUMN), dan neoliberalisme teknokratis (disiplin fiskal, daya tarik investasi asing).
Kondisi ini menimbulkan ambivalensi: ekonomi tumbuh stabil, tetapi legitimasi politik tetap rapuh karena rakyat kecil sering merasa tersisih.
Atas uraian tersebut, politik ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa kapitalisme negara, populisme fiskal, dan neoliberalisme teknokratis masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan.
1. Kapitalisme negara menciptakan pertumbuhan tinggi tetapi oligarkis;
2. Populisme Fiskal memperkuat legitimasi rakyat namun membebani fiskal ;
3. Neoliberalisme Teknokratis menjaga stabilitas makro namun menajamkan kesenjangan sosial.
Dalam konteks kontemporer, Indonesia tampak memilih jalan Hibridasi Ideologi ; menggabungkan unsur populisme, kapitalisme negara, dan neoliberalisme teknokratis. Namun, hibridasi ini belum mampu menjawab persoalan mendasar terkait ; ketimpangan, kedaulatan, dan legitimasi politik.
Perjalanan politik ekonomi Indonesia sampai saat ini, menunjukkan bahwa perubahan ideologi tidaklah absolut, melainkan adaptif terhadap kebutuhan rezim dan konteks global. Dari kapitalisme negara Orde Baru, populisme fiskal pasca-Reformasi, hingga neoliberalisme teknokratis, semua orientasi kebijakan bertujuan menjaga stabilitas politik, legitimasi rakyat, serta pertumbuhan ekonomi.
Saatnya Indonesia bangkit dengan melibatkan seluruh elemen rakyat dalam peran dan berpartisipasi aktif dengan inisiasi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan pelayan rakyat untuk melakukan dialog, diskusi, dan musyawah sebagai sarana silaturrahim dan juga media dalam menjawab dan merumuskan tantangan utama akan nasib dan masa depan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Republik Indonesia terkait sistem politik ekonomi berkeadilan sosial, berdaulat, sekaligus kompetitif di pasar global sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945.
Penulis : Abdul Rasyid Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawas
Editor : Natasya